Tikus-Tikus Sialan
Dilihat : 1221
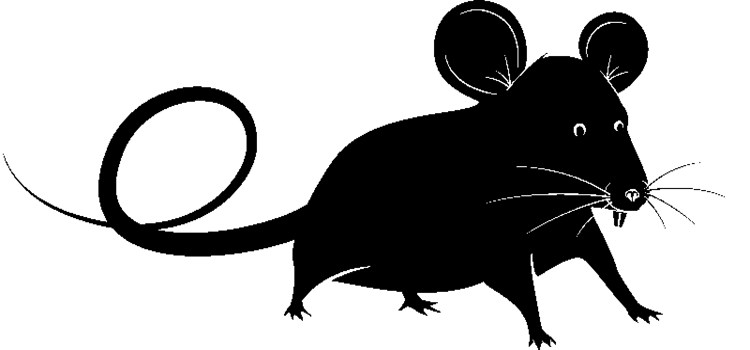
Mei selalu membuat Galang gusar. Ia meracau kepada istrinya, Arjanti, mengenai apa saja yang melintas dalam kepalanya seputar kejadian bulan Mei. Sementara Arjanti, melulu mengeluh soal tikus-tikus sawah yang selama bulan Mei agaknya makin payah dikendalikan. Begitulah mereka bertimbalan seolah topik itu koheren adanya. Pasalnya tabiat itu hanya muncul menjelang panen raya.
“Tikus kan memang begitu. Dia tahu di mana dan kapan pakan membeludak, disitulah dia membiak. Parasit!” serapah Galang. Ia lalu menenangkan diri dengan menghidu kopi racikan sang istri. Meski selalu beradu kata-kata, tak lantas menyurutkan niat baik wanita itu melayani suaminya yang menurutnya punya kegemaran di setiap bulan Mei: menjenguk kenangan lama.
“Aku sudah tanya mahasiswa PKL. Katanya tikus tidak suka pada kencing sapi, Pak.”
“Jelas-jelas antraks menyerang sapi-sapi belakangan ini. Darimana pula kita harus mencari kencingnya. Begitulah mahasiswa kalau tidak pelajari sejarah desa yang dituju, Bu,” keluh suami. “Janganlah terlalu diambil hati saran-saran mahasiswa PKL itu. Mahasiswa era ini tahunya kan cuma menyelesaikan tugas akhir secepat mungkin. Tak ada yang mau menembus isi kepala manusia-manusia di gedung kura-kura itu!” Nada pesimisme akut dilontarkannya setiap kali mendengar kata mahasiswa.
Lelaki setengah abad itu menentang langit. Di ujung pelupuknya, rundungan gerimis air mata mendesak membobol tapi egonya menahan. Entah apa gerangan yang membuatnya menjadi begitu sentimentil setiap kali bulan Mei tiba. Arjanti sangat tahu suaminya bergemuruh dan hanya bisa menepuk pundak pria itu sesekali. Kalau sudah begitu, ia tidak lagi berani menegasi ayat-ayat yang keluar dari mulut Galang. Ia hanya mendengarkan, seakan turut bertaut dalam kesedihan.
“Besok aku coba membunuh tikus-tikus itu dengan tanganku sendiri, Bu. Aku janji,” ujarnya seperti ingin menghalau kemelut pikiran yang membuatnya susah. Dua manusia itu, entah terjebak dalam gagasan atau sebenar-benarnya hama bernama tikus, tidak kunjung menemui ujung.
***
Ada yang gelisah di suatu siang yang berdarah. Sepasang mata tidak kedip mengawasi peristiwa mengerikan yang disiarkan di televisi hitam putihnya. Sudah dua bulan tak ada kabar dari sang putra. Entah anak itu ada di jalan mana, menyaru jadi apa, mengenakan pakaian apa, mengangkat umbul-umbul entahkah bendera. Yang pasti hati kecilnya yang terbuat dari zat maha tahu, seakan dapat merasa, telah terjadi sesuatu pada putra semata wayang.
Wanita itu melirik suami yang sudah tidak berdaya. Ia takut kalau-kalau takdir kematiannya telah mengintip di balik pintu, sementara ia tak dapat tahu keberadaan sang anak. Dalam kondisi begitu, ia nelangsa memikirkan manakah kejadian yang mengandung kebenaran. Mengizinkan anaknya terjun pada sesuatu –yang menurut anaknya itu- lebih luas dan besar maknanya dibandingkan nilai akademik pada kertas transkrip. Ataukah menyuruhnya pulang untuk melihat bapaknya yang terkapar, bernapas satu-satu, dan mungkin hanya menunggu saat kepulangannya saja.
Hingga sebuah kejadian membuat dadanya seperti ingin meledak. Berita nasional mengabarkan empat orang mahasiswa tewas terkena pelatuk aparat. Terkapar di jalanan, hanya karena berani bermulut lantang. Wanita itu panik, menangis, menjerit. Anakku, anakku! Tak henti ia meraung-raung membayangkan nasib tak pasti. Apakah putranya satu di antara mereka yang nyawanya turut terancam?
Seakan memang begitulah garis tangan telah menentukan. Alih-alih diberi waktu bagi air mata untuk kering, wanita itu justru makin sengsara karena suaminya sungguh dijemput kematian. Biarlah basah sekalian, pikir garis tangan, agar peristiwa luka-sembuh tidak mengulang dan terulang. Satu anaknya tak tahu rimba, lalu kini ditinggal suami menuju alam yang katanya baka. Waktu memaksanya untuk tak mendamba sama sekali apa yang tidak mungkin kembali.
Sepuluh tahun genap setelah peristiwa itu, sepucuk surat tua sampai ke rumah si wanita tua. Ia mengherani dan menduga surat itu salah alamat. Ia berasalan tak lagi punya sanak keluarga. Namun kurir pos yang wajahnya tak nampak begitu jelas, silau karena matahari, dengan tubuh yang gagah membentuk siluet, ngotot bilang benar. Mau tak mau ia terima, membawanya ke dalam rumah, meraih kacamata baca bekas sang suami, lalu membuka lipatannya.
Tak terbayang geluduk di hatinya.
IBU, ANAKMU SELAMAT. JANGAN KUATIR. HANYA SAMPAI PEMERINTAH MENGAMBIL LANGKAH SAJA, BU. SETELAH ITU, AKU JANJI AKAN PULANG. KATAKAN PADA BAPAK, MOHOH SABAR KARENA AKU AKAN MEMBACAKANNYA LAGI KISAH-KISAH TAN MALAKA. AH, BAPAK SEBENARNYA LEBIH SUKA MENYEBUTNYA ELIAS FUENTES. MAAFKAN ANAKMU IBU. AKU BERSALAH TELAH MENGABAIKANMU SEKIAN LAMA.
20 MEI 1998
Wanita tua meletakkan kacamata, tertatih mengejar si kurir. Memastikan ia datang bukan dari khayalan. Namun sang kurir tiba-tiba saja lenyap dalam kesunyian perkampungan. Seakan ia berasal dari alam yang berbeda. Surat itu telah memantik berjuta pertanyaan.
Secara mendadak ulu hati sang ibu malang nyeri tidak terperi, palpitasi jantungnya meningkat cepat, ia berusaha bernapas sekuat ia bisa, menahan kaki yang lemah, hingga akhirnya terjerembab di pinggir jalanan yang berdebu. Matanya membelalak berharap jangan mati sampai bertemu anaknya dahulu. Tapi garis tangan tak selalu setuju. Ia membeku. Terbujur kaku. Di jalanan itu.
***
“Pak, apa kita pakai racun saja? Tikus-tikus itu kelewat pandai mencari waktu. Entah apa yang ditakuti.”
“Mereka memang harus diracun dulu baru mati. Tapi kalau mereka mati, bukan berarti pekerjaan selesai, Bu. Kita masih harus dibuat lelah mencari bangkai,” jawab Galang sambil melingkari tanggal demi tanggal di kalender bulan Mei. Semuanya bertinta merah. Katanya bulan darah.
Sesungguhnya, persinggungan Arjanti dengan bulan Mei tak melulu soal ketakutan gagal dalam panen raya. Tapi Mei juga seakan membuatnya bersekat dengan sang suami. Kadang-kadang sulit baginya menghadapi keputusasaan Galang serta kemelut yang disimpannya di hati selama bertahun. Pria itu akan melancarkan aksi diam bila istrinya mencoba memintanya berdamai dengan masa lalu. Padahal niat Arjanti baik. Agar perasaan buruk itu tidak membukit dan jadi penyakit.
“Sampai kapan kau akan melingkari tanggal-tanggal itu? Tidak bisakah sedikit curahkan pengetahuanmu agar hasil tani kali ini berhasil?” Panas di hatinya akhirnya meluap. Galang spontan menghentikan jemarinya. Ia berbalik badan dan menetap lekat pada wajah istrinya.
“Kau sekarang berani mempertanyakan pengetahuanku?” Nada suaranya sinis, berat, pelan, mendalam.
“Sudah cukup, Pak! Kita tidak bisa berlama-lama hidup begini. Dirundung kepedihan bertahun-tahun seolah-olah kejadian itu baru terjadi kemarin. Belum cukup aku mengikutimu sampai kesini?” suaranya bergetar.
“Kau menyesal? Apa hidup dengan kapitalis-kapitalis menurutmu masih lebih jauh menyenangkan?”
Kata-kata Galang yang terdengar kasar berhasil menyinggung perasaannya. Ia lupa pada pengorbanan wanita itu, yang dengan sukarela mengikutnya dan wahamnya yang kuat mengakar. Bila ditarik jauh ke belakang, Galang-lah sesungguhnya alasan untuk ia berani meninggalkan segalanya yang tampak semarak di ibukota dan memilih tinggal jauh di perkampungan asal lelaki itu, yang baginya tak banyak beda dengan sebuah pelarian.
Untuk beberapa hari, rumah itu dirundung nestapa. Galang bungkam, Arjanti apalagi. Ia berhenti melingkari kalender. Istrinya pun tak sudi lagi mengurusi tikus-tikus di sawah. Saat tak sengaja mendengar berita di televisi berwarna, mengenai kilas-kilas balik tragedi Mei yang mencekam itu, Galang hanya bisa mengelus dada, tak lagi berani mengoceh. Seperti menimbunnya sendiri di dalam kotak pandora.
Sementara Arjanti kembali pada hobi lama. Membuat kristik atau sekadar bermuram durja ke arah jendela. Sudah mati rasa ingin tahunya mengenai cara membasmi hama tikus. Mahasiswa PKL yang datang ke rumah juga dihalaunya meski tak berkunjung perihal tata cara bertani.
Akan tetapi, mungkin didorong rasa cinta dan iba yang masih besar, keras hati itu seiring waktu melunak juga. Didorong rasa memiliki dan tak ingin lama dalam selisih, ketegangan itu lambat laun menjadi jinak.
“Tikus-tikus itu telah membunuh orangtuaku, sahabat-sahabatku. Segalanya mereka renggut tidak bersisa. Masakan tikus yang kau permasalahkan itu juga turut membuatku kehilanganmu?”
Di suatu senja yang sendu, Galang menghentikan tangan istrinya dari pemindangan lalu menautkannya. Berharap rasa hangat menjalari hati mereka berdua.
“Masih ada aku yang tersisa di antara teman-teman seperjuanganmu, Galang.”
“Maafkan aku, Arjanti. Maafkan aku terlambat sadar, masih ada kau disini. Kepalaku rasanya sulit menerima semua yang kucintai pergi tanpa bisa kembali.”
Galang menarik kepala wanita itu dan mendekatkannya ke dada. Hidup berdua hingga usia nyaris separuh abad, tanpa dikaruniai anak pula, membuat mereka seakan dipaksa keadaan untuk saling mengisi kekosongan yang ada. Dan kekosongan-kekosongan itu sesungguhnya residu dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang tak ingin mereka kenang.
“Kita jual saja sawah itu? Aku sudah habis akal merawatnya,” tanya Arjanti sambil berhamburan dalam pelukan suami. Membiarkan kain dan pemindangan berhamburan di atas lantai.
“Masa kau menyuruhku menjual negaraku?”
Mereka berdua tertawa, terhibur oleh metafora yang tercipta dengan sendirinya. Dilanjut mengenang masa-masa ketika mereka mahasiswa dulu. Tentang riak-riak demonstrasi dan tugas akhir yang tidak selesai.
“Tikus menyerang padi pada malam hari, siang hari ia sering bersembunyi di tangggul-tanggul irigasi. Kita harus waspada, Sayang!” Galang membelai lembut rambut istrinya.
Gagasan mereka tentang tikus tampaknya memang sama. Realitasnya saja yang tak serupa.
Medan, Juli 2023
Annie Maria Napitupulu






